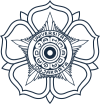Kemampuan komunikasi dan negosiasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang efektif. Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, M.A., dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM menyampaikan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal pandai berbicara namun mampu menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
“Kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan atau kuasa, melankan seni mempengaruhi orang lain agar mau bergerak mencapai tujuan,” jelasnya saat menjadi pembicara dalam Mandatory Softskill bertema “Communication and Negotiation Skill” pada Jum’at (31/10/2025) di Djarum Hall FEB UGM.
Ia menekankan bahwa gaya komunikasi dan cara bernegosiasi seorang pemimpin mencerminkan nilai-nilai kepemimpinannya. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak bisa dipisahkan dari karakter dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara itu, kampus merupakan ruang awal pembentukan karakter kepemimpinan. Di lingkungan akademik, mahasiswa memiliki kesempatan untuk melatih keberanian berpendapat, kemampuan menyampaikan ide secara logis, dan keterampilan bernegosiasi yang menghormati perbedaan.
Alfath juga mengajak mahasiswa untuk memahami realitas sosial Indonesia yang ia sebut sebagai paradoks “miskin, sakit, dan cerdas.” Menurutnya, tiga variabel ini, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan, adalah fondasi yang saling berkaitan. Keseimbangan ketiga aspek itu, lanjut Alfath, menjadi cermin kepemimpinan sejati yakni kepemimpinan yang berakar pada kepedulian sosial dan pemahaman terhadap persoalan masyarakat.
Lebih jauh, Alfath mengulas tantangan yang dihadapi kelompok rentan dalam perubahan sosial. Menurutnya, banyak kelompok yang tidak terlibat dalam proses perubahan karena tiga hal yaitu tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu. Seorang pemimpin harus mampu menjembatani ketiganya dengan komunikasi yang tepat dan tindakan nyata.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan. Tugas pemimpin adalah membuat mereka tahu, mau, dan akhirnya mampu,” tegasnya.
Fenomena krisis identitas di kalangan muda juga menjadi sorotan. Alfath memulainya dengan istilah yang cukup populer di lingkungan akademik yakni duck syndrome, kondisi di mana seseorang tampak tenang dan berhasil di permukaan, tetapi sebenarnya berjuang keras menahan tekanan di bawah. Fenomena ini, katanya, mencerminkan wajah generasi muda yang sering kali dituntut untuk selalu tampil sempurna, padahal sedang mengalami kebingungan mencari jati diri.
Menurutnya, krisis ini mencerminkan tantangan kepemimpinan generasi muda yang kehilangan keterhubungan dengan nilai-nilai budaya dan sosialnya. Kepemimpinan sejati lahir dari kesadaran akan realitas ini, dari kemampuan memahami diri sendiri, lingkungan, dan perubahan zaman.
“Kalau kita tidak tahu siapa diri kita dan untuk apa kita hidup, maka kita tidak akan bisa memimpin siapa pun,” tambahnya.
Di akhir acara, Alfath mengingatkan kembali pentingnya kemampuan berbicara dan bernegosiasi dalam berbagai situasi, baik di kampus maupun di dunia profesional. Ia mengutip pepatah, “The one who speaks wins,” yang menggambarkan bahwa keberanian menyuarakan gagasan dengan cara yang cerdas dan beretika adalah kunci untuk memengaruhi perubahan.
Reportase: Orie Priscylla Mapeda Lumalan
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals