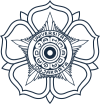Di lingkungan kampus yang penuh semangat dan pencapaian, ada satu fenomena yang sering tak terlihat, namun diam-diam dirasakan banyak mahasiswa yaitu duck syndrome. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika seseorang tampak tenang dan baik-baik saja dari luar, padahal sebenarnya sedang berjuang keras secara mental dan emosional.
Anisa Yuliandri, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dari Career and Student Development Unit (CSDU) FEB UGM mengatakan fenomena duck syndrome ini diambil dari metafora seekor bebek yang mengapung anggun di permukaan air, namun di bawahnya sedang mengayuh dengan panik agar tidak tenggelam. Fenomena ini semakin sering ditemukan di kalangan mahasiswa saat ini.
“Mahasiswa cenderung ingin tampil serba bisa, serba kuat, dan serba produktif. Tapi sayangnya, di balik semua itu, banyak yang merasa lelah dan kewalahan, namun tidak selalu mengetahui cara tepat untuk mengatasinya,” jelasnya.
Duck syndrome pertama kali digunakan untuk menggambarkan mahasiswa Stanford University yang tampak tenang namun sebenarnya berada di bawah tekanan. Kini, kondisi serupa ditemukan juga di berbagai kampus, termasuk di Indonesia. Mahasiswa berusaha memenuhi ekspektasi tinggi dari diri sendiri maupun lingkungan, mempertahankan IPK, aktif berorganisasi, magang, ikut lomba, hingga menjaga eksistensi di media sosial.
“Banyak mahasiswa merasa harus ambil semua kesempatan karena takut tertinggal. Takut kalau tidak ikut ini-itu nanti dibilang malas, tidak kompetitif, tidak punya masa depan,” lanjut Anisa.
Berdasarkan konsep Self-Determination Theory, manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu rasa kendali (autonomy), rasa mampu (competence), dan rasa terhubung (relatedness). Fenomena duck syndrome berkaitan erat dengan konsep ini, karena ketika pilihan hidup tidak lagi didasarkan pada keinginan pribadi melainkan pada tekanan eksternal, keseimbangan psikologis individu dapat terganggu.
Tidak hanya itu, budaya untuk selalu terlihat “baik-baik saja” juga membuat mahasiswa menekan atau menyembunyikan emosi yang sebenarnya mereka rasakan. Banyak yang merasa tidak boleh terlihat lelah atau menyerah, takut dianggap lemah. Anisa menambahkan bahwa perfeksionisme yang tinggi bisa membuat seseorang cenderung menutupi kelemahan dan kesulitan.
“Padahal kita manusia biasa, punya batas. Tapi karena ingin mempertahankan citra sempurna, akhirnya semua dipendam sendiri,” katanya.
Anisa menyebutkan bahwa keberadaan media sosial turut memperkuat tekanan ini. Ia mencontohkan ketika beranda media sosial seseorang dipenuhi dengan pencapaian orang lain seperti kemenangan lomba, pengalaman magang, kelulusan cepat, bahkan liburan, akan muncul perasaan tertinggal. Dalam usaha untuk tidak kalah bersinar, mahasiswa sering memaksakan diri untuk terlihat produktif.
“Ini sesuai dengan Impression Management Theory, yaitu kecenderungan individu untuk mengatur dan mengendalikan citra diri agar terlihat kuat dan mampu, meski di balik layar sedang sangat lelah,” ujar Anisa.
Anisa mengatakan duck syndrome bisa menjadi berbahaya karena sifatnya yang tak kasat mata. Karena tampak baik-baik saja, banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami distress psikologis. Kalimat seperti semua orang juga capek atau memang harus begini kalau mau sukses, menjadi pembenaran untuk terus memaksakan diri.
Padahal, menurut Anisa jika kondisi ini terus dibiarkan akan bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti kecemasan kronis, insomnia, burnout, bahkan depresi. Konflik perasaan internal dan ekspresi eksternal ini menciptakan disonansi kognitif yang berat. Lama-kelamaan seseorang bisa merasa asing dengan dirinya sendiri, bingung membedakan antara sibuk dan bahagia. Gejala duck syndrome juga memengaruhi hubungan sosial. Mahasiswa mulai menarik diri, merasa tidak cukup baik, dan menghindari interaksi.
“Ada perasaan takut dihakimi atau dianggap gagal, padahal sebetulnya yang dibutuhkan hanya ruang untuk didengar,” jelasnya.
Anisa menekankan pentingnya bagi mahasiswa untuk mulai mengenali gejala duck syndrome dan mengambil langkah kecil untuk mengatasinya. Langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa sedang lelah bukan kelemahan, justru merupakan bentuk keberanian.
“It’s okay to not be okay. Kita tidak harus selalu produktif atau terlihat bahagia. Mengizinkan diri merasa sedih adalah bagian dari pemulihan,” tuturnya.
Langkah berikutnya adalah mengelola ekspektasi, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Mahasiswa perlu menyadari bahwa tidak semua standar harus diikuti, dan tidak semua peran harus diambil. Menolak suatu tanggung jawab demi menjaga kesehatan mental adalah hal yang sah.
“Belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah adalah keterampilan penting,” tambah Anisa.
Anisa juga menekankan pentingnya berani bercerita. Bercerita kepada satu orang dapat sangat melegakan. FEB melalui CSDU menyediakan layanan konseling gratis yang dapat diakses oleh semua mahasiswa. Selain itu, FEB UGM juga memiliki program Peer Support, yakni teman sebaya yang telah dilatih untuk menjadi pendengar yang aman dan suportif.
“Tidak ada yang benar-benar baik-baik saja setiap saat. Kita tidak perlu berpura-pura kuat. Jika hari ini yang bisa kamu lakukan hanyalah bertahan, maka itu sudah cukup. Bertahan adalah bentuk keberanian,” tutup Anisa.
Reportase: Orie Priscylla Mapeda Lumalan
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals