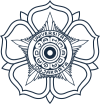Oleh: Wisnu Setiadi Nugroho
Departemen Ilmu Ekonomi, FEB UGM
Kepala Kelompok Kerja Transformasi Berkeadilan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS)
Saat Indonesia bergerak menuju status negara berpendapatan menengah atas, satu metrik penting masih tertinggal: garis kemiskinan kita. Selama lebih dari dua dekade, Indonesia telah menggunakan ambang batas yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menghitung pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan kalori dasar dan kebutuhan pokok non-makanan. Pendekatan ini, yang tidak berubah sejak 1998, memberikan konsistensi dalam pelacakan statistik. Namun, pertanyaannya kini bukan hanya seberapa banyak kalori yang dikonsumsi seseorang, tetapi apakah garis kemiskinan kita benar-benar mencerminkan arti hidup yang layak.
Garis Kemiskinan BPS: Lensa yang Terlalu Sempit
BPS menggunakan metode Kebutuhan Dasar (CBN), yang sangat menitikberatkan pada kecukupan kalori. Metode ini memperkirakan pengeluaran minimum bulanan untuk memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non-makanan. Per September 2024, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp595.242 per kapita, terdiri dari Rp443.433 untuk makanan (74,5%) dan Rp151.809 (25,5%) untuk kebutuhan non-makanan. Berdasarkan ukuran ini, 8,57% penduduk Indonesia diklasifikasikan sebagai miskin.
Dalam praktiknya, ini berarti seseorang yang hanya mengonsumsi nasi, minyak, dan mi instan dapat dianggap “tidak miskin,” meskipun mengalami kekurangan keragaman pangan atau gizi esensial. Meskipun CBN menawarkan tolok ukur statistik yang konsisten, pendekatan ini semakin dianggap terlalu sempit. CBN mengabaikan aspek kesejahteraan yang lebih luas, seperti kualitas gizi, akses terhadap layanan kesehatan, dan standar hidup dasar. Hal ini berisiko menutupi kerentanan dan gagal mencerminkan kesulitan sehari-hari jutaan orang yang secara teknis keluar dari garis kemiskinan, tetapi tetap hidup dalam kesehatan buruk, peluang terbatas, dan keterasingan sosial.
Garis Kemiskinan Bank Dunia: Dapat Dibandingkan Secara Global, Tapi Sering Disalahpahami Secara Lokal
Garis kemiskinan internasional Bank Dunia—US$2,15/hari (dalam PPP 2017)—banyak digunakan untuk perbandingan global. Namun, garis ini juga memiliki keterbatasan. Banyak yang keliru mengartikannya sebagai mencerminkan harga lokal, padahal sebenarnya menggunakan pendekatan paritas daya beli (PPP), yang menyesuaikan perbedaan tingkat harga antarnegara. Menurut estimasi Bank Dunia 2024, 1% penduduk Indonesia hidup di bawah garis US$2,15/hari. Dengan menggunakan konversi PPP sebesar Rp5.400 per US$1, maka garis ini setara dengan sekitar Rp11.600 per hari. Jika menggunakan garis negara berpendapatan menengah bawah (US$3,65/hari), angka kemiskinan naik menjadi 11,4%. Yang paling mencolok, jika menggunakan garis negara berpendapatan menengah atas (US$6,85/hari) — sekitar Rp37.000/hari — maka 50,1% masyarakat Indonesia berada di bawah ambang batas tersebut. Variasi besar ini menunjukkan betapa bergantungnya estimasi kemiskinan pada standar yang digunakan.
Lebih lanjut, keranjang PPP global dirancang untuk mencerminkan standar hidup minimum lintas negara. Namun, apa yang dianggap “dasar” di Jakarta bisa sangat berbeda dari di Kampala atau Kathmandu. Makanan pokok di satu negara bisa jadi barang mewah di negara lain. Harga protein, buah, atau bahan bakar sangat bervariasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun garis internasional berguna untuk perbandingan global, garis tersebut bisa menyesatkan jika dijadikan dasar untuk menilai kemiskinan lokal. Indonesia perlu memiliki standar yang mencerminkan realitasnya sendiri.
Garis Kemiskinan yang Mencerminkan Aspirasi Bangsa
Semakin banyak yang menyadari bahwa garis kemiskinan seharusnya mencerminkan bukan hanya kelangsungan hidup, tetapi juga martabat dan kesejahteraan. Seiring kemajuan ekonomi Indonesia, beberapa akademisi berpendapat bahwa pengukuran kemiskinan kita harus turut berkembang.
Arief Anshory Yusuf (2024) menyatakan bahwa garis kemiskinan resmi Indonesia masih sebanding dengan negara-negara berpendapatan rendah, meskipun kita telah diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pencapaian ekonomi kita dan cara kita mengukur kesulitan hidup. Ia menyarankan agar ambang batas dinaikkan agar sesuai dengan biaya hidup aktual dan ekspektasi sosial. Kristi Mahrt (2024) dari International Food Policy Research Institute (IFPRI) menawarkan alternatif yang menarik: garis kemiskinan yang sensitif terhadap gizi. Berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang (Permenkes No. 41/2014), ia mengusulkan garis kemiskinan yang memastikan asupan cukup dari semua kelompok makanan utama — kalori dan protein, sayur, buah, dan lemak sehat.
Pendekatan ini akan menaikkan ambang batas harian per kapita dari Rp20.000 menjadi sekitar Rp30.000–32.000. Kenaikan ini mencerminkan kenyataan bahwa makanan hewani dua kali lebih mahal, dan buah bisa sembilan kali lebih mahal dibanding makanan pokok dasar. Namun pendekatan ini juga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang apa yang dibutuhkan untuk mencegah stunting, wasting, dan kelaparan tersembunyi — yang semuanya masih menjadi masalah di Indonesia.
Menuju Ukuran yang Lebih Bermakna
Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa menaikkan garis kemiskinan hanya akan memperbesar angka kemiskinan. Namun, kekhawatiran ini melewatkan inti persoalan. Tujuan pengukuran kemiskinan bukanlah menghasilkan statistik yang indah, tetapi mencerminkan realitas. Garis kemiskinan yang lebih tinggi tidak menciptakan lebih banyak orang miskin — ia mengakui kedalaman kesulitan yang diabaikan oleh metrik saat ini.
Memperbarui garis kemiskinan tidak berarti harus membuang metode CBN yang ada. CBN tetap dapat digunakan untuk kesinambungan dan perbandingan historis. Namun, metode ini perlu dilengkapi dengan ukuran yang lebih komprehensif, yang memperhitungkan gizi, kesehatan, dan dimensi kesejahteraan lainnya. Sebagaimana kita melacak baik PDB maupun PNB, kita juga dapat melacak tingkat kemiskinan berbasis kalori dan yang sensitif terhadap gizi secara paralel. Pada akhirnya, memperbarui garis kemiskinan bukan hanya soal teknis, tetapi juga sebuah keharusan moral dan kebijakan. Untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, alat pengukuran kita harus mencerminkan biaya hidup yang nyata, bukan sekadar biaya bertahan hidup.
Indonesia telah mencatat kemajuan besar dalam pengentasan kemiskinan. Namun untuk menjaga momentum tersebut — dan memenuhi tujuan kita dalam pembangunan manusia, kesetaraan, dan pertumbuhan inklusif — kita harus menyelaraskan definisi dan data kita dengan realitas sehari-hari yang dihadapi masyarakat Indonesia. Hanya dengan cara itulah kita bisa mengklaim bahwa kita sedang membangun masyarakat di mana setiap orang memiliki peluang, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang.
*Telah dipublikasikan di The Jakarta Post (5 Mei 2025) dan Tempo.co (3 Mei 2025)