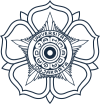Oleh: Muhammad Edhie Purnawan (Departemen Ilmu Ekonomi, FEB UGM)
Prolog
Trump dan Powell adalah kawan. Dulu. Trump mengusulkan Powell menjadi Chairman The Fed pada 2 November 2017, periode pertamanya sebagai presiden Amerika. Selang beberapa waktu, Trump menjadi lawan Powell, lalu Trump ingin memecat Jay, meski kemudian melunak. Hal ini diutarakan beberapa kali di depan media. Dua nakhoda ini, saat ini, sedang menavigasi kapal yang sama. Namun mereka saling bertentangan.
Trump bak pelaut tangguh, ingin memacu kapal cepat melaju. Dia menggunakan indikator tarif dan stimulus fiskal untuk menjalankan kapalnya. Semuanya demi kesejahteraan umum. Dan untuk bertindak, dia gunakan U.S. Constitution Preamble dan Employment Act 1946. Di lain pihak, Powell menavigasi kapal yang sama dengan sangat berhati-hati, menjaga stabilitas kapal beserta para penumpangnya. Dia gunakan kompas data dan peta kebijakan, demi penyerapan tenaga kerja maksimal. Kepatuhan Powell pada Federal Reserve Act dan Humphrey-Hawkins Act, tak diragukan.
Adalah Donald John Trump, pengusaha sukses dan bintang televisi yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 2017, dan ke-47 pada 2025, membawa gaya kepemimpinan yang non-konvensional dan penuh gebrakan di Gedung Putih.
Berbeda dari para pendahulunya yang pada umumnya berlatar belakang politik atau akademis, Trump bangkit dari dunia properti dan hiburan, membangun kerajaan bisnis dengan merek “Trump” yang ikonik itu, sebelum akhirnya dia melompat ke dunia politik. Dan dengan pendekatannya yang berani dan sering kali terlihat provokatif, ia menentang tradisi dengan memberikan kritik terbuka kepada kebijakan Federal Reserve, menekan chairman Fed Powell untuk menurunkan suku bunga melalui cuitan dan pernyataan yang heboh.
Trump memperjuangkan agenda deregulasi dan perang dagang agresif, mengenakan tarif pada mitra dagang seperti Tiongkok, dan memicu ketidakpastian ekonomi global.
Meski menuai kontroversi, pendekatannya yang disruptif—dari nominasi anggota Fed yang tidak biasa hingga negosiasi perdagangan yang keras—mencerminkan visinya menggoyang status quo dan memprioritaskan kepentingan AS.
Berbeda dengan Trump, Jerome Hayden “Jay” Powell adalah lulusan Princeton dan Georgetown Law yang pernah menjadi editor jurnal hukum, membawa warna baru sebagai chairman Federal Reserve pada 2018. Lalu berbeda pula dari para pendahulunya yang bergelimang gelar doktor bidang ekonomi (yang memang jadi nilai tambah), Powell datang dengan pengalaman mentereng di dunia investment banking, ekuitas swasta di The Carlyle Group, dan posisi senior di Departemen Keuangan era George H. W. Bush.
Dengan pendekatannya yang pragmatis, ia memimpin the Fed dengan komitmen kuat terhadap independensi, mengarungi kompleksitas pasca quantitative easing dan gejolak pasar 2013.
Awalnya, dia skeptis terhadap pembelian aset, Powell lalu berubah pikiran saat data membuktikan manfaatnya, menunjukkan fleksibilitas dalam merangkul fakta. Di tahun-tahun awal, ia tak hanya fokus pada kebijakan moneter, tetapi juga menyelami detail teknis regulasi keuangan, membuka babak baru yang transformatif.
Sayangnya, antara Presiden dan Gubernur bank sentral AS sering terjadi konflik. Trump kembali menyatakan ingin memecat Powell pada awal 2025, lalu baru saja dia berbalik arah, tidak jadi menghentikan Powell, karena juga tidak mungkin itu bisa dilakukan. Tapi, barangkali, dia nanti akan balik haluan lagi, ingin memecat lagi—seperti periode Trump pertama dulu. Dan Powell bersiteguh melaksanakan tugas hingga 2026.
Bentrokan mereka laksana dua gelombang besar yang bertabrakan, tentu mengguncang kapal besar, kapal perekonomian AS. Dan ini sudah terjadi dalam beberapa hari. Ini bukan soal pribadi, melainkan pertarungan dua visi. Apakah ekonomi harus melayani ambisi politik jangka pendek, ataukah ia menjaga keseimbangan yang lebih lama?
Untuk memahami dinamika hubungan antara Presiden dan Gubernur bank sentral AS, agar kita bisa mengambil hikmah dan kebijaksanaan. Karena itu maka kita perlu belajar dari interaksi mereka saat ini, maupun di masa lampau.
Karena itu, kita bisa merujuk karya monumental Alan S. Blinder, Wakil Gubernur The Fed (1994-1996), profesor ilmu ekonomi dari Princeton University. Karyanya cukup monumental: A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961–2021 (2022). Blinder menyajikan narasi otoritatif tentang enam dekade kebijakan moneter dan fiskal AS, dari era Kennedy, hingga respons Biden terhadap pandemi.
Melalui pengalamannya sebagai orang dalam, Blinder menguraikan interaksi kompleks antara dua belas presiden dan delapan gubernur The Fed, termasuk William McChesney Martin hingga Jerome Hayden Powell. Dia juga menelusuri peristiwa penting seperti stagflasi pada 1970-an, kebangkitan Reaganomics, krisis keuangan 2008, dan kebijakan moneter selama pandemi Covid-19. Lalu dengan fokus pada perubahan jangka panjang, Blinder tidak hanya menjelaskan wawasan tentang sejarah perekonomian AS secara mendalam, tetapi dia juga menerangkan pelajaran berharga, untuk memahami ketegangan kontemporer Trump-Powell.
Akar Konflik Kebijakan
Trump memandang pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan keberhasilan kepemimpinannya. Dalam The Art of the Deal (1987), ia menekankan kehandalan insting dan negosiasi sebagai elemen kunci. Pada 2017, ia meluncurkan Tax Cuts and Jobs Act, yang memangkas pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%, mendorong investasi dan konsumsi, meski defisit anggaran meningkat (April 2025).
Pada pertengahan April 2025, Trump memberlakukan tarif tinggi—hingga 145 persen lalu 245 persen untuk impor Tiongkok, 32 persen untuk produk Indonesia, dan 10 persen untuk semua impor, seperti disampaikan oleh The White House—untuk melindungi industri domestik (khususnya baja dan otomotif) serta mengurangi defisit perdagangan $1,2 triliun (Politico, 5 Februari 2025).
Namun, tarif ini diperkirakan meningkatkan pengangguran sebesar 0,6 persen atau sekitar 770,000 pekerjaan hilang, dan harga konsumen naik sebesar 3 persen, mengganggu rantai pasok global, dan memicu risiko resesi (CSIS, 2025), menandakan gejala stagflasi, inflasi tinggi dengan laju ekonomi tumbuh melambat.
Lebih jauh tentang konflik ini, sejak tahun 1961, hubungan antara Presiden AS dengan Gubernur The Fed telah bergeser dari pengaruh kuat politik menuju independensi bank sentral yang matang.
Blinder mengupas periode ketika kebijakan fiskal dan moneter selaras ataupun saat keduanya bertentangan, memberikan pelajaran berharga bagi perselisihan saat ini, ketika Trump menyatakan lagi ingin memecat Powell, yang seolah tak peduli terhadap gubernur The Fed.
Lalu, bagaimana respon masyarakat tentang ini sebelum hari ini? Untuk itu, ada yang menarik dari penelitian oleh Kuttner dan Posen (2007), yang melihat bagaimana kepedulian pasar terhadap seorang gubernur bank sentral, tetap intensif. Tulisan mereka tentang “Do Markets Care Who Chairs the Central Bank” yang dimuat pada NBER Working Paper Series menunjukkan bahwa pengangkatan gubernur bank sentral oleh presiden AS benar-benar dicermati oleh pasar. Lalu setelah menjabat beberapa waktu, pasar akan menilai preferensi kebijakan gubernur baru secara cermat, berdasarkan informasi yang tersedia.
Di era Nixon-Burns sebagai Presiden dan Gubernur The Fed, hubungan keduanya memperlihatkan campur tangan politik yang berbahaya. Nixon menunjuk Burns, sekutu dekatnya, dengan harapan Burns bisa menjaga suku bunga rendah untuk mendukung pemilihan ulangnya pada 1972. Burns memenuhi harapan Nixon dengan kebijakan moneter longgar, meningkatkan pasokan uang M1 dan M2, serta menurunkan suku bunga federal ke 3,5% pada Januari 1972.
Hasilnya, pertumbuhan ekonomi melonjak, namun inflasi meningkat, memicu stagflasi pasca-kejutan minyak OPEC 1973. Konflik ini menunjukkan bagaimana tekanan politik merusak stabilitas ekonomi jangka panjang.
Lalu era Clinton-Greenspan tahun 1990-an, sebaliknya, menunjukkan keeratan yang efektif. Clinton mengejar pengurangan defisit anggaran, sementara Greenspan menyesuaikan suku bunga secara berhati-hati, menjaga inflasi tetap rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 1993 Clinton mengikuti saran Greenspan untuk memangkas defisit hingga sebesar $140 miliar. Hal ini memicu reli pasar obligasi dan menurunkan suku bunga, yang merangsang ekspansi ekonomi panjang.
Kerjasama ini menghasilkan “long boom” dengan inflasi rendah, pengangguran minimal, dan pertumbuhan kuat. Dari keduanya, kita bisa belajar manfaat koordinasi keduanya, yang tidak mengorbankan independensi The Fed.
Lain lagi era Carter-Volcker. Pada akhir tahun 1970-an. Carter meminta Volcker untuk memerangi inflasi. Meskipun kebijakan Volcker saat itu super ketat—menaikkan suku bunga federal fund hingga 17,6 persen pada tahun 1980, hingga menyebabkan resesi, Carter tetap mendukungnya. Mereka memprioritaskan stabilitas ekonomi jangka panjang. Independensi The Fed kuat, meskipun secara politik, ini merugikan Carter. Jelas ini berkebalikan dengan Nixon-Burns, ketika tekanan politik masuk ke ranah moneter.
Pada era Reagan-Volcker, presiden yang pada awalnya mendukung Volcker untuk menekan inflasi, namun kebijakan fiskal Reagan malah terlalu ekspansif. Dia memotong pajak dan menambah pengeluaran untuk pertahanan. Hal ini bertentangan dengan kebijakan moneter ketat Volcker (bahkan FFR pernah 19,1 persen pada Juni 1981). Ketegangan sempat meningkat, ketika staf presiden mencoba memengaruhi Volcker untuk tidak menaikkan suku bunga menjelang pemilu 1984. Tapi Volcker bergeming. The Fed tetap independen.
Pada akhirnya, secara keseluruhan, kerjasama antara Volcker dan Reagan bisa menurunkan inflasi, setelah terjadi defisit anggaran besar akibat resesi 1981-1982.
Lalu saat ini, kepemimpinan Powell terus diuji oleh serangan-serangan verbal Trump yang tak biasa, melanggar tradisi seorang presiden yang biasanya menahan diri. Dari cuitan yang mengkritik kenaikan suku bunga, hingga ancaman penurunan jabatan, Trump menyentak independensi Fed. Namun, Powell menjawab dengan cerdik dan santun: menggelar konferensi pers rutin untuk menjelaskan kebijakan dengan bahasa sederhana, rajin menjalin hubungan dengan Kongres untuk dukungan lintas partai, dan menolak terpancing provokasi. Pada 2019 dulu, ia bahkan pernah melakukan manuver brilian—menghentikan kenaikan suku bunga dan meluncurkan tiga pemotongan “asuransi” untuk merespons ketidakpastian perang dagang dan kurva hasil terbalik, mencegah perlambatan ekonomi. Bersamaan dengan itu, ia memimpin tinjauan strategi Fed dengan acara “Fed Listens” yang melibatkan publik, memperkuat pendekatan inklusif dan berbasis data. Ini sangat menginspirasi.
Dan pada 2025 ini juga, konflik Trump-Powell mencerminkan ketegangan historis yang terjadi sebelumnya, antara presiden dengan kepala otoritas moneter. Dengan pendekatan proteksionis, Trump meluncurkan tarif tinggi pada 17 April 2025—245% kepada Tiongkok (Reuters), dengan alasan untuk melindungi industri lokal dan mengurangi defisit perdagangan. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, kebijakan ini mampu menciptakan 198,000 lapangan kerja di sektor manufaktur hingga Maret 2025. Namun, harga barang melonjak. Artikel “The China Shock” dalam NBER, 2019, menjelaskan semua tentang hal ini.
Selain daripada itu, Powell lebih fokus pada stabilitas jangka panjang. Sebagai gubernur The Fed, ia bertugas menjaga inflasi rendah dan lapangan kerja maksimal.
Dalam pidato di Jackson Hole, wilayah Barat Laut Wyoming, pada Selasa 17 Juli 2018, Powell menegaskan bahwa seluruh keputusannya selalu berbasis data, bukan berdasarkan tekanan politik. Pendekatan yang dilakukannya berhasil menjaga inflasi di bawah 2,5 persen pada saat itu, di tengah meningkatnya stimulus fiskal Trump yang berlebihan.
Ketegangan Klasik Fiskal-Moneter
Adalah Jan Tinbergen, pemenang Nobel ekonomi 1969, dalam On the Theory of Economic Policy, menyatakan bahwa untuk mencapai sejumlah tujuan ekonomi—seperti pertumbuhan, lapangan kerja, dan stabilitas harga (3 objectives)—pemerintah memerlukan setidaknya jumlah instrumen kebijakan yang sama atau lebih banyak dibandingkan jumlah tujuan tersebut. Misalnya, kebijakan fiskal, moneter, dan suku bunga (3 instrumen).
Lalu Trump menggunakan tarif dan memotong pajak untuk mendorong pertumbuhan dan mendorong penyerapan tenaga kerja. Sementara Powell, fokus pada suku bunga dan jumlah uang beredar, untuk mengejar stabilitas harga. Ini jelas berseberangan. Konflik ini dapat dipahami melalui teori ekonomi moneter dan fiskal.
Di dalam The Fiscal Theory of the Price Level yang merujuk, salah satunya, dari Leeper (1991), menegaskan bahwa kebijakan fiskal, seperti tarif Trump, dapat memengaruhi tingkat harga jika anggaran pemerintah tidak seimbang. Tarif ini meningkatkan harga impor, mendorong inflasi, hingga menjadi tantangan bagi Powell untuk menjaga target inflasi tetap di kisaran 2%.
Pandangan monetaris Milton Friedman, pemenang Nobel ekonomi 1976, dalam The Role of Monetary Policy, sesungguhnya mendukung Powell. Friedman menegaskan bahwa kebijakan moneter adalah alat utama untuk mengendalikan inflasi, bukan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dengan fokus pada stabilitas harga, Powell menjaga ekonomi dari spiral inflasi yang merusak, mencerminkan disiplin Friedman. Prinsip ini menjadi benteng bagi Powell dalam menghadapi tekanan politik, memastikan kapal ekonomi tetap stabil di tengah badai ketidakpastian.
Sementara itu, Robert Lucas, yang juga pemenang Nobel ekonomi 1995, dalam Econometric Policy Evaluation (1976) sudah pernah mengingatkan, bahwa ekspektasi rasional masyarakat dapat mengurangi efektivitas kebijakan, sehingga harus otoritas harus berhati-hati mengelola ekspektasi pelaku ekonomi, karena tarif ini bisa memicu ekspektasi inflasi yang lebih tinggi, sehingga melemahkan upaya untuk stabilisasi harga.
Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif agresif Trump ini tentu memperumit tantangan ini, menuntut Powell untuk berkomunikasi dengan pasar lebih kuat guna mengendalikan ekspektasi inflasi. Dengan demikian, pendekatan Powell yang berbasis data menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah inflasi yang spiral.
Dari sisi perdagangan internasional, Paul Krugman, Nobel Laureate bidang trade (2008), dalam Increasing Returns and Economic Geography, menekankan bagaimana gangguan perdagangan, seperti tarif, dapat memicu kenaikan harga yang memperburuk tekanan inflasi, merusak stabilitas ekonomi secara luas. Kebijakan proteksionisme, misalnya, tidak hanya mengganggu aliran barang tetapi juga memperumit upaya bank sentral untuk menjaga stabilitas harga. Krugman memperingatkan bahwa efek skala ekonomi dalam perdagangan global dapat memperkuat dampak negatif ini, karena gangguan rantai pasok cenderung memicu efek domino yang memperparah ketidakstabilan harga di pasar internasional.
Ancaman Stagflasi
Stagflasi—kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan lambat—adalah ancaman nyata. Pada 1970-an, tekanan Presiden Nixon pada Ketua The Fed Arthur Burns untuk menjaga suku bunga rendah memicu inflasi dua digit, sebagaimana dicatat Meltzer dalam A History of The Federal Reserve.
Konflik Trump-Powell ini mirip, dengan Trump mendorong kebijakan ekspansif yang berisiko memperburuk inflasi. Penelitian Barsky dan Kilian (2004) dalam Journal of Economic Perspectives menunjukkan bahwa stagflasi 1970-an tidak memerlukan guncangan pasokan minyak, seperti embargo OPEC, melainkan dapat dijelaskan oleh ekspansi moneter global dan shock di sisi permintaan. Sebaliknya, tarif Trump pada 2025, yang meningkat dari 145% menjadi 245% (Tiongkok), juga menciptakan guncangan serupa dengan menaikkan harga impor dan memperlambat perdagangan global.
Laporan Current Policy Perspectives Fed Boston pada April 2025 mencatat bahwa perusahaan kecil dan menengah khawatir terhadap tarif yang ditetapkan, karena akan meningkatkan biaya input dan harga jual—konsisten dengan kekhawatiran Powell.
Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, kebijakan Trump yang mendorong patriotisme ekonomi ini memang telah meningkatkan produksi baja 8% sejak 2024 dan menciptakan 198,000 lapangan kerja di sektor manufaktur. Namun, defisit perdagangan AS-Tiongkok telah naik dari US$279,4 miliar (2023) menjadi US$298 miliar (2024).
Lalu, tarif mendadak ini meningkatkan harga konsumen dan diperkirakan menambah beban rumah tangga di AS, meski Powell telah mampu menjaga stabilitas, menahan inflasi di bawah 3 persen (dari 2,8 persen turun menjadi 2,4 persen). Namun demikian, bayang-bayang stagflasi masih bisa mengintai, menantang Powell untuk terus menavigasi kapal ekonomi AS di tengah badai ketidakpastian ini.
Secara demikian, untuk mengatasi dampak ini, kombinasi (policy mix) kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan fiskal yang lebih kuat, menjadi sangat penting, di tengah tantangan yang semakin rumit—dengan kebijakan tarif yang tinggi—yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi lebih lanjut.
Karena itu, dalam 90 hari jeda ini diharapkan Trump bisa menyederhanakan tarif secara bertahap, beralih ke insentif pajak untuk mendukung industri manufaktur tanpa mengganggu tata-struktur perdagangan internasional, sekaligus memperbaiki hubungan dengan chairman The Fed.
Lalu Powell pun jika terdesak, harus bisa menyesuaikan komunikasi, seperti yang dilakukan oleh Mario Draghi di ECB yang ikonik itu, di satu momen pada 2012, ketika berjanji untuk melakukan “whatever it takes” untuk menyelamatkan euro, yang menenangkan pasar tanpa forward guidance formal. Hal ini telah menunjukkan kewibawaan Draghi dalam mengelola ekspektasi (Reuters, 2016).
Pun demikian, dengan Trump, sebaiknya Powell juga melakukan dialog informal—seperti yang dilakukan antara Greenspan dengan Clinton—yang bisa menyelaraskan visi tanpa mengorbankan independensi The Fed.
Kebijakan berbasis aturan atau Rules Based Policy (misalnya, Taylor rule, McCallum rule, Ball rule, Svensson rule, Walsh rule, Galí rule, dan lainnya), mestinya bisa mengurangi ketidakpastian. Hal ini sangat diminati oleh Powell, meski Powell juga menekankan perlunya koordinasi kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas moneter yang terkoordinasi.
Dan dia pun membuktikan, bahwa tantangan teknis dapat diselesaikan, seperti misalnya gejolak pasar repo pada 2019, semakin memamerkan ketangguhan Powell. Kekeliruan dalam memperkirakan cadangan yang cukup memicu lonjakan suku bunga repo, namun Powell dengan sigap mengintervensi, memperluas neraca Fed dan menstabilkan pasar lewat operasi terarah.
Episode ini, ditambah dengan kemampuannya menavigasi dampak perang dagang Trump dan ketidakpastian tarif, menegaskan kelihaian Powell menyeimbangkan krisis jangka pendek dengan visi jangka panjang.
Pada 2020, kebijakannya berhasil menciptakan soft landing, menggemakan kesuksesan Alan Greenspan di era 1990-an, sekaligus memperkokoh peran The Fed sebagai penjaga stabilitas ekonomi yang tangguh di tengah badai politik.
Maka, di tengah pertempuran visi ini, dunia sekali lagi menyaksikan, akankah kapal mereka terus menemukan keseimbangan, atau terkoyak dalam badai yang sulit lagi dikendalikan? Ketegangan antara Trump dan Powell ini mencerminkan pergulatan antara ambisi pertumbuhan dan stabilitas.
Melalui tarif tinggi untuk semua impor, Trump berupaya memacu industri domestik dan lapangan kerja, namun mendongkrak inflasi hingga 3 persen pada Januari, 2025. Sebaliknya, Powell berjuang menjaga inflasi mendekati 2 persen, memastikan stabilitas keuangan, dan juga mendukung penyerapan pada lapangan kerja, meskipun pernyataannya kerap memicu kebingungan pasar (Bloomberg, 2025).
Tanpa koordinasi dan sinergi kebijakan, dialog terbuka, dan komunikasi yang jelas, risiko stagflasi masih bisa terjadi—dengan inflasi melonjak, pengangguran naik atau banyak pekerjaan hilang di AS, kemudian pertumbuhan terhambat.
Epilog
Tampaknya, Trump bagai armada kolosus, mengarungi lautan ekonomi dengan tembakan retorika yang mengguncang. Layar ambisinya terbentang lebar, menantang badai perdagangan dan bertekad menyeret para pemimpin global masuk ke dalam cakrawala dominasinya. Namun, Powell, Sang nakhoda Federal Reserve yang tangguh, memegang erat-erat kemudi, berjuang melawan pusaran pasar dan karang politik, mengantar perekonomian ke arah stabilitas.
Perseteruan kehendak mereka telah menggoyang kapal Amerika: ancaman Trump untuk memecat Powell memicu kegusaran pasar, merontokkan harga saham dan obligasi. Karena itu, hanya satu kehendak yang mungkin survive, tak bisa keduanya, atau pasar lagi yang akan karam. Dan terbukti: ancaman penyingkiran itu telah menggetarkan pasar Amerika.
Lalu tampak jelas, pada akhirnya, Presiden pun terdesak. Namun sayangnya, kita semua sama sekali tidak bisa meramal suasana hati Sang Don, besok pagi.
*Telah dipublikasikan di infobanknews.com
Sustainable Development Goals