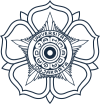Oleh: Wisnu Setiadi Nugroho
Departemen Ilmu Ekonomi, FEB UGM
Ketua Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS)
Angka itu mungkin terlihat kecil: turun 1,2 juta orang dalam setahun. Namun di balik statistik tersebut, ada jutaan cerita tentang keluarga yang harus menunda membeli rumah, orang tua yang mulai ragu menyekolahkan anaknya ke kampus impian, dan pekerja yang merasa posisinya makin rapuh. Laporan Mandiri Institute menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk turun dari 17,1% menjadi 16,6%.
Pada saat yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) melonjak 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4% populasi. Artinya, lebih dari separuh warga Indonesia hidup tepat di bawah ambang kelas menengah, cukup dekat untuk naik, tetapi cukup rentan untuk jatuh kembali. Ini bukan sekadar soal statistik. Ini soal rasa aman.
Kelas menengah adalah kelompok yang biasanya merasa “cukup”: cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan, cukup untuk bermimpi lebih besar dari orang tuanya. Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan.
Dalam studi Who is the Middle Class and Why Should We Care?, ditunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia memang relatif tipis dan banyak berada di batas bawah (lower middle class). Artinya, fondasinya rapuh. Sedikit saja guncangan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), biaya sekolah naik, cicilan naik, dapat mendorong mereka turun kelas. Membesarnya AMC hari ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian.
Mengapa Ini Terjadi?
Pertama, karena pekerjaan yang tersedia semakin tidak menjanjikan mobilitas. Dalam riset From Survivability to Mobility, terlihat bahwa banyak lapangan kerja baru bersifat survival-based—cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk naik kelas. Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas. Orang bekerja keras, tetapi tangga sosialnya tidak bertambah panjang.
Kedua, daya beli tergerus perlahan. Upah riil kelas menengah bawah relatif stagnan, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat. Ini bukan kemerosotan dramatis, melainkan tekanan senyap income squeeze, yang menggerogoti kemampuan menabung dan merencanakan masa depan. Banyak keluarga masih terlihat “baik-baik saja”, tetapi ruang napas fiskal dan keuangannya semakin sempit.
Ketiga, meningkatnya pekerjaan rentan berbasis rumah tangga. Studi Demystifying Home-Based Jobs menunjukkan banyak pekerjaan semacam ini tidak dilengkapi jaminan sosial. Ketika sakit datang atau permintaan melemah, tidak ada bantalan. Satu guncangan kecil bisa menggugurkan stabilitas yang dibangun bertahun-tahun.
Keempat, kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah. Kebijakan sosial masih berfokus pada kelompok miskin, yang tentu saja masih harus dilindungi. Namun AMC yang kini menjadi mayoritas populasi berada dalam wilayah abu-abu: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup aman untuk mandiri sepenuhnya. Mereka berdiri sendirian ketika risiko datang. Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial.

Inilah risiko terbesar: aspiration without mobility. Aspirasi masyarakat tinggi, anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi tangga strukturalnya tidak tersedia. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, kita berhadapan dengan jebakan mobilitas. Dalam jangka panjang, fondasi konsumsi dan basis pajak melemah, dan transformasi menuju negara maju kehilangan penopang utamanya. Pertumbuhan ekonomi penting. Namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku.
Kita Membutuhkan Respons yang Lebih Berani
Pertama, menciptakan pekerjaan yang benar-benar membuka mobilitas, manufaktur bernilai tambah, jasa modern, dan sektor dengan produktivitas tinggi. Pendidikan vokasi harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas kurikulum. Kedua, membangun bantalan risiko bagi aspiring middle class. Jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial perlu menjangkau pekerja non-formal. Skema pembiayaan perumahan dan pendidikan harus dirancang agar kelompok near-middle tidak tergelincir hanya karena satu guncangan.
Ketiga, memastikan kebijakan dirancang untuk mobilitas, bukan sekadar redistribusi jangka pendek. Bantuan sosial perlu dievaluasi agar tidak menciptakan cliff effect, di mana sedikit kenaikan pendapatan justru membuat perlindungan hilang seluruhnya. Kita tidak boleh membiarkan aspiring middle class menjadi kelas rentan permanen. Penyusutan kelas menengah hari ini bisa menjadi sinyal awal dari stagnasi struktural yang lebih dalam.
Kelas menengah bukan hanya kategori statistik. Ia adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan yang paling penting, penjaga optimisme sosial. Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar angka 1,2 juta. Yang hilang adalah keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik daripada hari ini.