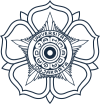Sistem pembayaran digital domestik yaitu Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena kemudahan yang ditawarkan melainkan kritik dari pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menilai penerapan QRIS membatasi ruang gerak pelaku industri global. Kritik ini dimuat dalam laporan National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada akhir Maret 2025.
Berikut petikan wawancara dengan Dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Nofie Iman Vidya Kemal, S.E., M.Sc., Ph.D., yang mendalami kajian Manajemen Teknologi dan Studi Inovasi pada Rabu 23 April 2025 terkait dengan polemik QRIS ini.
Bagaimana Bapak melihat kritik yang dilayangkan AS terhadap kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia, khususnya QRIS dan GPN sebagai hambatan perdagangan?
Tidak banyak yang bisa dibanggakan dari kebijakan pemerintah belakangan ini, tetapi khusus QRIS/GPN harus diacungi jempol. QRIS dan GPN adalah bentuk ketahanan dan kedaulatan di bidang ekonomi. Logikanya sederhana: pembeli dan penjual di Indonesia, barang di Indonesia, transaksi pakai rupiah, mengapa payment gateway dan settlement harus lewat luar negeri?
GPN mungkin “hanya” bisa di-expand sebanyak jumlah masyarakat Indonesia. Kendati begitu, QRIS sebagai payment gateway dan settlement mechanism mempunyai potensi untuk di-expand lebih luas karena negara lain sebenarnya juga punya common interest terhadap dedolarisasi. Singapura punya SGQR dan PayNow, DuitNow di Malaysia, Vietnam ada VietQR, ada Thai QR dan PromptPay di Thailand, dan seterusnya.
Apabila peluang ini ditangkap oleh semua negara ASEAN, mengingat besarnya market dan jumlah pengguna, penggunaan QRIS bisa makin meluas termasuk hingga Korea Selatan, Jepang, China, dan UAE. Kondisi tersebut menjadikan transaksi via USD akan berkurang signifikan dan ketergantungan kita terhadap USD juga akan menurun. Ini akan menciptakan efek bola salju yang luar biasa dan pukulan telak bagi MasterCard/VISA.
Dalam konferensi pers RDG BI pada Oktober 2024, jumlah pengguna QRIS mencapai 54,1 juta dengan jumlah merchant 34,7 juta. Jumlah transaksi uang elektronik meningkat 27,0 persen (Year on Year/ YoY) menjadi 1.365,4 juta transaksi, tetapi penggunaan kartu ATM atau kartu debit hanya 558,8 juta transaksi atau turun 11,4 persen (YoY). Jadi kita bisa berhipotesis bahwa terjadi pergeseran dari transaksi kartu ATM atau kartu debit yang sebagian menggunakan MasterCard/VISA) ke QRIS.
Walau demikian, menurut saya, hambatan perdagangan antara AS dan Indonesia bukan terletak pada GPN/QRIS. Hambatan justru di faktor lain seperti ketidakpastian hukum, banyaknya pungutan liar, KKN, pelanggaran hak cipta/pembajakan, dan sebagainya. Kritik AS terhadap QRIS/GPN rasanya lebih karena (1) berkurangnya porsi keuntungan yang diperoleh MasterCard/VISA, (2) ketidakmampuan mereka untuk mengakses/analisis data transaksi (market intelligence), dan (3) ancaman terhadap supremasi USD.
Hal ini terlihat dari kritik AS yang dilayangkan tidak hanya ke Indonesia, tetapi juga ke negara-negara lain yang memiliki sistem payment/settlement independen seperti Thailand, Vietnam, India, Meksiko, dan lain-lain. Singkat kata, ini kritik yang mengada-ada. Ini adalah bentuk economic coercion. Dan kalau AS sampai sudah merasa “terganggu”, bisa jadi kita sebenarnya sudah berada “dijalan yang benar.”
Lantas apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap kritik yang dilayangkan AS ini?
Pertama-tama, jangan terlalu reaktif dan berlebihan menanggapi isu ini. Pertama, foreign trade barrier report-nya USTR sebenarnya sudah diterbitkan sejak lama dan ada segudang keluhan dan concern sejak dulu yang terus menerus muncul dan tidak pernah benar-benar diperbaiki oleh pemerintah kita. Kedua, kritik ini dalam beberapa hal ada benarnya. Misalnya, mesin tiket di stasiun KA Bandara Soetta hanya memberikan opsi pembayaran QRIS. Ini tentu merepotkan bagi orang asing yang tidak punya QRIS.
Namun terlepas dari itu semua, kembali ke GPN/QRIS, bank-bank di Indonesia saat ini masih menawarkan VISA dan MasterCard sebagai opsi payment gateway. GPN hanya didesain untuk skala nasional. Cross-border QRIS juga saat ini baru terbatas ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Harusnya deal ini masih fair dan jadi valid point negosiasi. Ini juga sesuai spirit pasar bebas yang digaungkan AS: sediakan pilihan, biarkan konsumen memilih.
Tidak ada yang melarang perusahaan/organisasi/warga AS untuk menggunakan QRIS. Kalau mau, MasterCard/VISA juga bisa membuka diri, mengembangkan API/interface atau global protocol supaya bisa terhubung ke GPN kita. Mereka juga bisa bekerja sama dengan mitra lokal, lalu bergabung ke jaringan GPN. Jangan sampai MasterCard/VISA dikecualikan atau diberi keistimewaan dibanding yang lain.
Presiden Prabowo mengatakan kita adalah negara besar, macan Asia. Ini saatnya untuk membuktikan pidato beliau tidak sekedar omon-omon saja. Tidak sekadar yes man, yes sir, saja. Jangan sampai baru digertak langsung menyerah begitu saja. Dan semoga menteri dan negosiator yang diutus presiden benar-benar mampu menegosiasikan ini semua.
Sejauh mana manfaat QRIS dan GPN bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal inklusi keuangan dan efisiensi transaksi?
QRIS adalah bentuk frugal innovation. Inovasi yang sederhana, hanya memerlukan ponsel yang masyarakat kita sudah memilikinya, tetapi berdampak luas dan disruptif. Dampaknya juga terasa, masyarakat kita mengalami transisi menuju cashless society dan semua ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Menurut Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), tahun 2020 transaksi QRIS hanya 124 juta dengan nominal Rp8,2 triliun; tahun 2024 sudah jadi 6,24 miliar transaksi dengan nilai Rp695,9 triliun.
Penjual gorengan, bubur ayam, pedagang pasar, warteg/angkringan bahkan hingga kotak infaq di masjid (inclusivity) bisa menerima pembayaran cashless tanpa harus mengeluarkan biaya (affordability) untuk mesin point-of-sales (PoS), Electronic Data Capture (EDC), kartu berbasis chip, dan lainnya. Pembayaran dilakukan hanya melalui ponsel, tidak perlu infrastruktur baru (adaptability). Inclusivity + affordability + adaptability = frugal innovation.
Kesederhanaan QRIS menunjukkan bahwa alat ini memang didesain untuk mendorong inklusi keuangan. Dari sisi pengguna, saat membayar di warung misalnya, kita hanya membayar nominal tagihan tanpa tambahan biaya. Tidak ada biaya admin atau top-up, kecuali kebijakan spesifik dari penyedia dompet digital atau transfer antar bank. Dari sisi merchant, biaya transaksi 0,3-0,7% per transaksi (tergantung kebijakan bank/e-wallet). Transaksi Rp 100.000 dikenakan biaya Rp 300-700. BI bahkan mendorong biaya serendah mungkin, bahkan 0% bagi usaha mikro. Tidak ada biaya untuk mendaftar QRIS atau mencetak kode QR. Biaya hanya muncul jika merchant meminta layanan tambahan seperti sistem POS digital.
Bandingkan dengan VISA/MasterCard. Pengguna tidak kena biaya untuk transaksi domestik biasa, namun bisa terkena 1-3% dari transaksi jika menggunakan kartu di luar negeri atau bertransaksi dalam mata uang asing. Biaya tahunan kartu bervariasi mulai dari Rp 0 untuk kartu dasar hingga jutaan rupiah untuk kartu premium. Penarikan tunai di ATM bisa 2-5% dari jumlah penarikan. Bagi merchant, ada biaya transaksi 1,5-3,5% per transaksi untuk kartu kredit dan 0,5-1,5% untuk kartu debit tergantung negara dan jenis usaha. Transaksi Rp 100.000 dengan kartu kredit dikenakan biaya Rp 1.500-3.500. Masih ada biaya tambahan seperti sewa/setup mesin EDC yaitu Rp 50.000-200.000 per bulan, cross-border atau tambahan 1-2% jika menerima pembayaran dari kartu luar negeri, dan interchange fee yang dibayarkan ke bank penerbit kartu (termasuk dalam biaya transaksi di atas).
Informasi dari beberapa vendor menyatakan bahwa waktu penerimaan dana via QRIS lebih cepat. Bahkan beberapa bank menawarkan tidak hanya same-day settlement, tapi juga settlement hingga 3-4 kali sehari. Jika rekening bank merchant berbeda dengan penyedia QRIS, transaksi terjadi di hari libur, atau terjadi masalah verifikasi/kesalahan teknis, maka settlement bisa memakan tambahan 1-2 hari.
Angka ini masih lebih baik dibanding waktu penerimaan dana di VISA/MasterCard yang bisa 1-3 hari kerja dalam kondisi standar. Untuk transaksi internasional atau memerlukan konversi mata uang dan jaringan antar bank, waktu yang diperlukan bisa 3-7 hari kerja
Bagaimana sistem pembayaran domestik ini mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan pemberdayaan UMKM di Indonesia?
Menurut saya, dampak terbesar QRIS adalah sifatnya yang universal yaitu 1 kode QR untuk semua bank/merchant sehingga mendorong adopsi di sisi demand dan keberpihakan terutama kepada UMKM dengan biaya murah atau bahkan nol sehingga mendorong adopsi dari sisi suplai. QRIS juga mendapatkan momentumnya karena berbarengan dengan pandemi COVID-19 – kita membutuhkan solusi contactless yang aman dan mengurangi penggunaan uang tunai. Jadilah QRIS meledak jumlah penggunanya. Proses onboarding menuju QRIS jadi sangat smooth.
Mungkin QRIS/GPN tidak secara langsung berkontribusi pada ekonomi digital, namun QRIS/GPN membantu mempercepat transformasi digital, terutama pada UMKM. Biaya integrasi yang rendah membuat UMKM bertransformasi lebih cepat. Selain itu, dengan beralih ke switching domestik, biaya operasional penyedia jasa keuangan menurun, yang pada gilirannya dapat diteruskan ke konsumen lewat tarif transaksi yang lebih kompetitif. Ini berarti meningkatkan efisiensi keseluruhan ekonomi termasuk digital nasional.
Bagaimana kebijakan ini dapat melindungi kepentingan nasional di tengah tekanan globalisasi dan dominasi korporasi multinasional?
Dalam konsep digital sovereignty, sudah menjadi hak suatu negara untuk mengendalikan aliran data dan infrastruktur digitalnya demi keamanan, kedaulatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum hadirnya GPN, transaksi domestik kerap dirutekan melalui jaringan internasional seperti (SWIFT, MasterCard/VISA, dan lainnya, yang memungut Merchant Discount Rate (MDR) tinggi dan mencatat data kita di server asing. Korporasi multinasional di sektor pembayaran dengan skala dan modal globalnya yang luar biasa dapat memengaruhi kebijakan domestik melalui lobbying dan tekanan pasar, sehingga mereduksi ruang manuver negara kita untuk mengatur tarif dan keamanan data.
Bank Indonesia, melalui PBI No. 19/8/2017, mewajibkan lembaga switching GPN berizin lokal dan membatasi kepemilikan asing hingga 20%, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan infrastruktur pembayaran domestik. Semua penyelenggara QRIS wajib menerapkan standar nasional. Otomatis hal ini mempersatukan ekosistem dan menurunkan biaya integrasi bagi merchant serta fintech lokal. Interoperabilitas GPN serta QRIS, yang hanya memerlukan satu stiker QR pada merchant, bersama‑sama meningkatkan efisiensi biaya dan akses bagi UMKM tanpa bergantung pada EDC impor. Lagi-lagi, ini sejalan dengan prinsip digital sovereignty.
Bagaimana sebaiknya Indonesia menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap pelaku internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam sektor pembayaran digital? Bagaimana menyeimbangkan inovasi dan regulasi serta rekomendasi strategis bagi pemerintah?
Dalam bahasa Belanda ada istilah “Het recht hink achter de feiten aan.” Hukum selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya. Dalam hal teknologi, tak mungkin aturan tentang misalnya cryptocurrency muncul dulu sebelum inovasinya. Pasti muncul belakangan. Pertanyaannya, berapa besar gap atau celah tersebut?
Bank Indonesia punya blueprint sistem pembayaran di Indonesia 2025. OJK menerbitkan blueprint transformasi digital perbankan. Kominfo dulu merilis visi Indonesia digital 2045. Sepanjang yang saya ketahui, kita belum memiliki roadmap pengembangan ekonomi digital yang benar-benar komprehensif. Masih terjebak pada silo-silo yang tidak terintegrasi dengan baik atau berpotensi overlap satu sama lain. Ini PR utama kita, membuat roadmap yang benar-benar komprehensif dan terintegrasi, tapi juga dijalankan secara konkrit, tidak sekadar formalitas atau administratif saja.
Di level teknis, kita harus memiliki kerangka regulasi, apalagi terkait pembayaran digital yang lebih adaptif, forward-looking, terukur, dan berbasis prinsip reciprocity. Pemerintah juga perlu mengembangkan regulatory sandbox untuk menguji setiap inovasi sebelum diluncurkan secara luas ke masyarakat. Meskipun saat ini sudah dijalankan BI/OJK, tetapi kedepan perlu diperluas juga ke sektor lain. Mekanisme tiered licensing atau pembatasan kepemilikan asing di 20% memastikan bahwa kontrol strategis tetap di tangan kita.
Negara harus hadir bukan saja untuk menjamin kepentingan nasional, tetapi lebih penting lagi, untuk menjamin distribusi sumberdaya yang adil dan merata. Jangan sampai inovasi dan regulasi yang dijalankan malah memperlebar inequality. Selain itu, negara juga harus berani berdiri tegak melawan kolonialisme digital. Kalau sendirian saja, kita memang sangat vulnerable terhadap tekanan koersif AS, tapi beda ceritanya kalau kita bergandengan tangan dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals