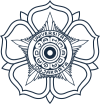Oleh Elan Satriawan & Wisnu Setiadi Nugroho
Departemen Ilmu Ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam visi Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045. Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan, guna mengatasi malnutrisi kronis dan stunting yang menghambat potensi sumber daya manusia Indonesia. Namun, peluncuran awal program ini mengungkap pelajaran berharga bagi perluasan kesejahteraan di negara berkembang yang kompleks. Hingga September 2025, MBG telah menjangkau 22,7 juta penerima manfaat melalui 7.644 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target 32.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun. Namun, hingga 8 September, hanya Rp 13 triliun, atau sekitar 18,3% dari anggaran Rp 71 triliun, yang telah disalurkan. Tingkat penyerapan yang rendah ini menyoroti hambatan logistik, koordinasi, dan administratif yang serius yang mengancam kredibilitas program.
Dilema Distribusi
Meskipun sebagian besar SPPG awalnya didirikan di daerah yang mudah diakses, di mana infrastruktur dan logistik seharusnya paling mudah dikelola, program ini tetap mengalami kegagalan serius dalam pengendalian kualitas. Banyak unit menghadapi penundaan transfer dana, hambatan dalam pengadaan, dan inefisiensi distribusi yang mengganggu distribusi makanan. Wabah keracunan makanan massal telah menimpa siswa lebih dari 1.000 anak sakit di Jawa Barat dalam beberapa minggu terakhir, yang merupakan salah satu dari banyak insiden serupa. Sejak program diluncurkan, lebih dari 6.400 anak telah terinfeks. Investigasi oleh lembaga pemerintah telah mengonfirmasi bahwa kurangnya pengawasan dan kelalaian prosedural berkontribusi pada wabah ini, termasuk waktu memasak yang tidak konsisten, makanan yang busuk, dan sertifikasi dapur yang tidak memadai. Uji laboratorium mendeteksi kontaminasi dari E. coli, Salmonella, dan Bacillus cereus, mengungkap kelemahan sistemik dalam penanganan makanan, manajemen rantai dingin, dan mekanisme pengawasan.
Insiden-insiden ini mengungkap masalah mendasar: bahkan dalam kondisi yang menguntungkan, jaminan kualitas belum diterapkan dengan baik. Bayangkan jika kegagalan semacam ini terjadi di wilayah yang sudah siap. Apa yang akan terjadi ketika program ini diperluas ke daerah terpencil, di mana biaya pemantauan lebih tinggi, rantai pasokan lebih lemah, dan pengawasan lokal terbatas? Tanpa perlindungan yang kuat, memperluas program terlalu cepat dapat memperbesar risiko daripada memberikan manfaat. Program yang dirancang untuk memberi nutrisi seharusnya tidak pernah membahayakan. Tugas pemerintah saat ini bukanlah mempercepat peluncuran program, melainkan menghentikan sementara, mundur selangkah, dan mengevaluasi ulang, memastikan keamanan pangan dan akuntabilitas sebelum perluasan apa pun.
Ketika Penyaluran Lambat Menghambat Pertumbuhan
Di luar masalah operasional, kinerja buruk MBG memiliki konsekuensi makroekonomi. Pengeluaran pemerintah adalah mesin vital pertumbuhan domestik, dan ketika penyaluran terhenti, stimulus fiskal melemah. Hingga September, hanya sebagian kecil dana MBG yang mencapai ekonomi lokal. Analis dan kementerian keuangan menunjuk pada penyerapan lambat di program-program unggulan, termasuk MBG, sebagai faktor yang mengurangi likuiditas dan memperlambat pertumbuhan. Pelaksanaan program yang buruk secara efektif meredam efek penggandaannya.
Kementerian Keuangan mengakui bahwa belanja yang lambat di berbagai program besar, termasuk MBG, telah mengurangi likuiditas dan menunda transmisi fiskal. Faktanya, pada Juni 2025, pemerintah baru menyalurkan Rp 4,4 triliun (≈ 2,6% dari anggaran) untuk MBG. Kinerja yang kurang optimal ini menekan perekonomian lokal yang seharusnya dapat diuntungkan dari belanja melalui pembelian pangan, logistik, dan upah. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan untuk 2025 direvisi turun menjadi ~4,8%, dengan pelaksanaan belanja publik yang kurang optimal disebut sebagai salah satu hambatan.
Biaya Ambisi Tanpa Ketepatan
Bobot fiskal MBG sangat besar, sekitar lima hingga enam kali lipat dari alokasi untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan subsidi pendidikan serupa. Meskipun hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah terhadap gizi dan kesetaraan, hal ini juga menuntut kehati-hatian dan ketepatan dalam pelaksanaan. Penyaluran yang lambat telah meredam momentum pengeluaran publik, sementara ketidakefisienan berisiko menggeser investasi kritis lainnya di ruang kelas, guru, dan infrastruktur.
Pendekatan universal juga menimbulkan masalah keadilan yang serius. Argumen keadilan memerlukan tinjauan lebih lanjut. Menurut Survei Susenas 2024, kurang dari 3% anak melaporkan ketidakamanan pangan yang parah, kehabisan makanan, merasa lapar tanpa makan, atau melewatkan makan sepanjang hari. Bahkan di kalangan rumah tangga miskin, tingkatnya sekitar 6–7%. Karena kelompok ini merupakan minoritas, desain program makan gratis universal berisiko menjadi tidak efisien dan regresif, menguntungkan anak-anak yang tidak memerlukan dukungan gizi.
Fase konsolidasi sementara bukanlah langkah mundur, melainkan koreksi kebijakan yang bertanggung jawab. Menunda perluasan program memberikan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang paling penting: keamanan pangan, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Selama evaluasi ulang ini, pemerintah dapat menguji model distribusi yang lebih terfokus, memprioritaskan siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat atau yang tercantum dalam Daftar Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu anak-anak yang paling berisiko mengalami kekurangan gizi. Memanfaatkan data DTSEN akan memungkinkan MBG menargetkan rumah tangga yang benar-benar membutuhkan bantuan, memastikan sumber daya terbatas diarahkan ke tempat yang dapat memberikan dampak terbesar.
Memperbarui Strategi Pelaksanaan
Desain sama pentingnya dengan kapasitas. Indonesia juga perlu mengevaluasi kembali model pelaksanaan Program Pemberian Makanan di Sekolah (PBMS). Struktur SPPG yang terpusat saat ini mungkin tidak optimal untuk negara sebesar dan seberagam Indonesia. Secara global, program pemberian makanan di sekolah beroperasi berdasarkan dua pendekatan utama: sistem terpusat, di mana makanan disiapkan di fasilitas berskala besar dan didistribusikan ke sekolah-sekolah, dan sistem desentralisasi, di mana sekolah atau komunitas lokal mengelola proses memasak dan distribusi. Setiap model memiliki kelebihannya. Sentralisasi memastikan keseragaman dan pengawasan, sementara desentralisasi mendorong akuntabilitas, fleksibilitas, dan relevansi lokal. Bagi Indonesia, model hibrida yang menggabungkan pedoman gizi standar dengan implementasi berbasis komunitas mungkin menawarkan keseimbangan terbaik antara efisiensi dan inklusivitas.
Indonesia dapat belajar dari program sosialnya sendiri: PKH dan BPNT. Keduanya dimulai sebagai pilot skala kecil, menjalani evaluasi ketat, dan diperluas secara nasional setelah menunjukkan dampak yang terukur. MBG harus mengikuti jalur yang sama: bukti terlebih dahulu, perluasan kemudian. Pemerintah dapat memanfaatkan fase konsolidasi ini untuk menguji model pengiriman yang berbeda, terpusat, desentralisasi, dan hibrida di seluruh provinsi untuk menentukan pendekatan mana yang memberikan hasil terbaik dalam hal keamanan, biaya, dan hasil gizi.
Selain itu, implementasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Mengambil contoh dari sistem makan siang sekolah berbasis komunitas di Jepang, komunitas, sekolah, dan orang tua dapat lebih terlibat dalam persiapan makanan, pengawasan, dan penyesuaian. Dapur lokal akan mengurangi biaya logistik, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan pertanggungjawaban. Akhirnya, pengadaan bahan baku secara lokal sangat penting. Program PNAE Brasil mewajibkan minimal 30% bahan baku makanan sekolah berasal dari petani kecil. Secara keseluruhan, reformasi ini akan mengubah MBG dari program sosial murni menjadi inisiatif pengembangan ekonomi dan komunitas yang lebih luas, yang tidak hanya memberi makan anak-anak tetapi juga menghidupkan kembali pertanian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kepercayaan sosial.
Pelajaran Regional dan Langkah ke Depan
MBG adalah salah satu investasi sosial terberani Indonesia, inisiatif yang secara langsung menghubungkan gizi, pendidikan, dan produktivitas. Sedikit program yang begitu jelas menggambarkan gagasan bahwa pengembangan manusia dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Namun, ambisi yang mendefinisikan MBG kini berisiko melemahkannya. Kekurangan keamanan pangan, penargetan yang buruk, dan penyaluran yang lambat telah melemahkan kepercayaan publik dan meredam dampaknya terhadap pembangunan. Untuk melindungi baik warga maupun kredibilitas, pemerintah harus menghentikan sementara, mundur selangkah, dan menyesuaikan kembali.
Periode refleksi ini tidak boleh menghentikan kemajuan, melainkan mengarahkannya. MBG dapat terus beroperasi dalam skala yang lebih kecil dan strategis, memprioritaskan daerah-daerah dengan kebutuhan tinggi sambil menyempurnakan sistem pengadaan, protokol keamanan pangan, dan model distribusi. Memberikan gizi yang baik kepada anak-anak bukan sekadar intervensi kesejahteraan; ini adalah kewajiban moral dan perkembangan. Janji program ini hanya akan terwujud ketika setiap makanan yang disajikan bergizi, aman, dan tepat sasaran, serta ketika rantai pasokannya juga memberdayakan petani lokal dan usaha kecil. Itulah cara MBG benar-benar dapat beralih dari kebijakan ke piring, dan dari niat baik ke dampak yang berkelanjutan.
Pengalaman Indonesia juga memberikan pelajaran bagi upaya perluasan kesejahteraan yang lebih luas di Asia Tenggara. Di seluruh kawasan, pemerintah belajar bahwa ambisi tanpa ketepatan dapat berbalik arah menguras anggaran, merusak kepercayaan, dan melemahkan hasil sosial. Ekspansi cepat tanpa penargetan yang kuat, standar keamanan, dan evaluasi berisiko mengubah program transformatif menjadi kisah peringatan yang mahal. Sebaliknya, mereka yang berinvestasi dalam uji coba, kepemilikan lokal, dan desain berbasis bukti dapat mempertahankan kredibilitas fiskal dan kepercayaan publik.
Memberikan gizi yang baik kepada anak-anak bukanlah sekadar ujian nasional; ini merupakan ukuran seberapa efektif ekonomi Asia yang sedang berkembang mengubah pengeluaran sosial menjadi keuntungan modal manusia jangka panjang. Jika diterapkan dengan disiplin dan bukti, MBG dapat menjadi model regional untuk pertumbuhan inklusif, bukti bahwa perlindungan sosial dapat menjadi adil dan efisien. Jika tidak, hal ini mungkin menjadi pengingat bahwa niat baik, tanpa ketepatan dan tata kelola yang baik, jarang menghasilkan hasil yang baik.