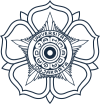Di balik keindahan motif batik yang lahir dari tradisi turun-temurun, tersimpan dilema besar yaitu limbah pewarna kimia yang kerap mencemari sungai di sekitar sentra produksi. Pertanyaan pun muncul, haruskah warisan budaya dibayar dengan kerusakan alam?
Guru Besar bidang Inovasi dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Nurul Indarti, Sivilokonom., Cand.Merc., Ph.D., menyampaikan bahwa batik bukan sekedar kain, tetapi sebuah warisan budaya yang diakui oleh UNESCO sekaligus menjadi identitas bangsa. Lebih dari itu, batik telah menjadi sumber penghidupan jutaan orang di tanah air yang mayoritas adalah perempuan. Namun, permintaan global saat ini tidak hanya menekankan pada keindahan motif, tetapi juga menuntut proses produksi yang ramah lingkungan.
“Jawaban dilema ini ada pada inovasi hijau. Upaya mengurangi dampak negatif lingkungan melalui produk, proses, maupun model bisnis baru,” ucapnya.
Menurutnya, transformasi menuju inovasi hijau dalam batik tidak dapat dipandang hanya sebagai strategi bisnis adaptif. Ia adalah perwujudan nyata dari pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan sekaligus upaya menjaga martabat budaya Indonesia di tengah tuntutan keberlanjutan global.
Nurul menyebutkan inovasi hijau dalam batik hadir melalui penggunaan pewarna alami dari indigo, secang hingga daun jati. Lalu pengolahan limbah batik dengan biofilter dan fitoremediasi. Berikutnya implementasi prinsip ekonomi sirkular dengan mengubah kain perca menjadi tas, aksesori, hingga dekorasi rumah.
Lantas mengapa para perajin batik atau usaha kecil menengah batik memilih jalan hijau? Dari riset yang dilakukan oleh Nurul dan tim di lapangan diketahui bagaimana inovasi hijau dipahami dan dijalankan oleh usaha kecil menengah (UKM) batik di Indonesia. Nurul menjelaskan ada tiga kerangka teori untuk membantu memahami hal tersebut. Pertama, teori determinasi diri. Beberapa pengrajin batik dengan tegas memilih jalur hijau bukan karena keuntungan jangka pendek, melainkan karena keyakinan moral dan spiritual.
“Mereka merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Motivasi intrinsik ini menjadi energi jangka panjang, meskipun biaya tinggi dan akses teknologi terbatas,” jelasnya.
Kedua, teori institusional. Nurul menyebutkan tekanan dari luar memaksa UKM bertransformasi seperti regulasi seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, tuntutan masyarakat lokal yang menolak pencemaran, dan praktik pesaing yang berhasil menembus pasar internasional. Tekanan koersif, normatif, dan mimetik inilah yang mendorong perubahan.
“Ketiga, triple bottom line. Bahwa inovasi hijau harus menghasilkan nilai pada tiga dimensi sekaligus yaitu profit, planet, dan people. Dengan cara ini, praktik hijau bukan hanya kewajiban,
tetapi strategi bisnis yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan,” paparnya.
Ia pun menceritakan sejumlah kisah inspiratif dari UKM batik di Indonesia yang memperlihatkan bagaimana inovasi hijau dijalankan. Paradise Batik berhasil meraih Sertifikat Industri Hijau dan menembus pasar internasional dengan kombinasi praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, dan narasi keberlanjutan. Kemudian, Smart Batik yang menonjol dengan inovasi batik sawit sekaligus melakukan integrasi proses produksi yang menekan limbah serta Kampung Harapan Ponorogo yang melibatkan pengrajin difabel.
Nurul menyebutkan yang membuat batik hijau istimewa bukan semata teknologinya, tetapi kisah yang melekat padanya. Mulai dari kisah budaya seperti motif sebagai doa, filosofi, dan identitas. Lalu kisah alam meliputi warna alami dari daun, kayu, dan bunga hingga kisah etika seperti produksi yang inklusif, adil, dan memberdayakan perempuan serta difabel.
“Kisah-kisah yang mencakup budaya, alam, dan etika produksi ini menegaskan bahwa tuntutan pasar bergerak seiring dengan praktik keberlanjutan. Konsumen global tidak hanya membeli produk berdasar fungsi, namun juga membeli kisah yang melekat di dalamnya,” jelasnya.
Nurul menyadari jalan menuju batik hijau tidaklah mudah. Sejumlah tantangan struktural, kultural, dan pasar masih membatasi transformasi ini. Biaya dan akses teknologi menjadi kendala utama. Investasi untuk instalasi pengolahan limbah (IPAL) membutuhkan biaya besar.
“Persoalan lain adalah keterbatasan pengetahuan teknis dan resistensi kultural. Lalu, persepsi pasar domestik yang masih meragukan kualitas eco-batik dan belum ada standar nasional yang jelas sehingga risiko greenwashing muncul,” imbuhnya.
Kondisi dengan keterbatasan tersebut, lanjutnya, memunculkan strategi bagi para perajin batik. Ada yang memilih ambidexterity yaitu dengan tetap memproduksi batik konvensional untuk pasar domestik sambil mengembangkan eco-batik untuk pasar premium internasional. Sementara lainnya ada yang beralih penuh ke pewarna alami dan ada pula yang bergotong royong membangun IPAL komunal.
Nurul menyebutkan bahwa tantangan ini bukanlah akhir cerita, melainkan pemicu inovasi yang menjadikan eco-batik sebagai lokomotif daya saing budaya sekaligus simbol keberlanjutan Indonesia di pasar global. Beberapa refleksi yang sebaiknya dilakukan adalah dengan menguatkan motivasi berbasis nilai, mengarahkan tekanan institusional agar produktif, membangun standarisasi dan sertifikasi yang inklusif, dan memanfaatkan triple bottom line sebagai kompas strategi. Penting juga untuk melakukan kolaborasi lintas pihak antara UKM dengan dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat, universitas, pemerintah, dan mitra swasta.
Reportase: Shofi Hawa Anjani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals